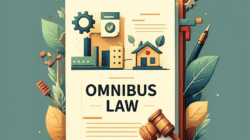UU ITE: Pedang Bermata Dua Kebebasan Berekspresi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai payung hukum di era digital. Tujuan mulianya adalah menciptakan ruang siber yang aman dari kejahatan seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Namun, dalam implementasinya, UU ITE kerap memicu perdebatan sengit, khususnya terkait batas-batas kebebasan berekspresi.
Di satu sisi, UU ITE memang berfungsi melindungi individu dari fitnah atau ujaran kebencian di dunia maya. Ia memberikan landasan hukum bagi korban untuk mencari keadilan atas kerugian digital yang dialaminya. Ini adalah aspek positif yang tak bisa diabaikan dalam menjaga ketertiban ruang siber.
Namun, di sisi lain, beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan berita bohong, sering dianggap sebagai ‘pasal karet’ yang multitafsir. Penerapannya kerap berujung pada kriminalisasi kritik yang sah, pendapat yang berbeda, atau bahkan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan publik atau pihak tertentu. Akibatnya, muncul ‘efek gentar’ (chilling effect) yang membuat masyarakat enggan menyuarakan pendapatnya secara bebas karena khawatir terjerat hukum.
Dilema utama terletak pada pencarian keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan ruang digital dan menjaga ruang demokrasi tetap terbuka bagi kebebasan berekspresi. Implementasi UU ITE seharusnya tidak menjadi alat pembungkam, melainkan instrumen yang mendorong pertanggungjawaban digital tanpa mengebiri hak fundamental warga negara untuk berpendapat.
Maka, diperlukan pemahaman dan tafsir yang lebih adil serta reformasi berkelanjutan terhadap UU ITE. Tujuannya adalah memastikan undang-undang ini benar-benar berfungsi melindungi, bukan membatasi. Kebebasan berekspresi adalah pilar penting demokrasi; menjaganya tetap hidup di era digital adalah tanggung jawab kita bersama.